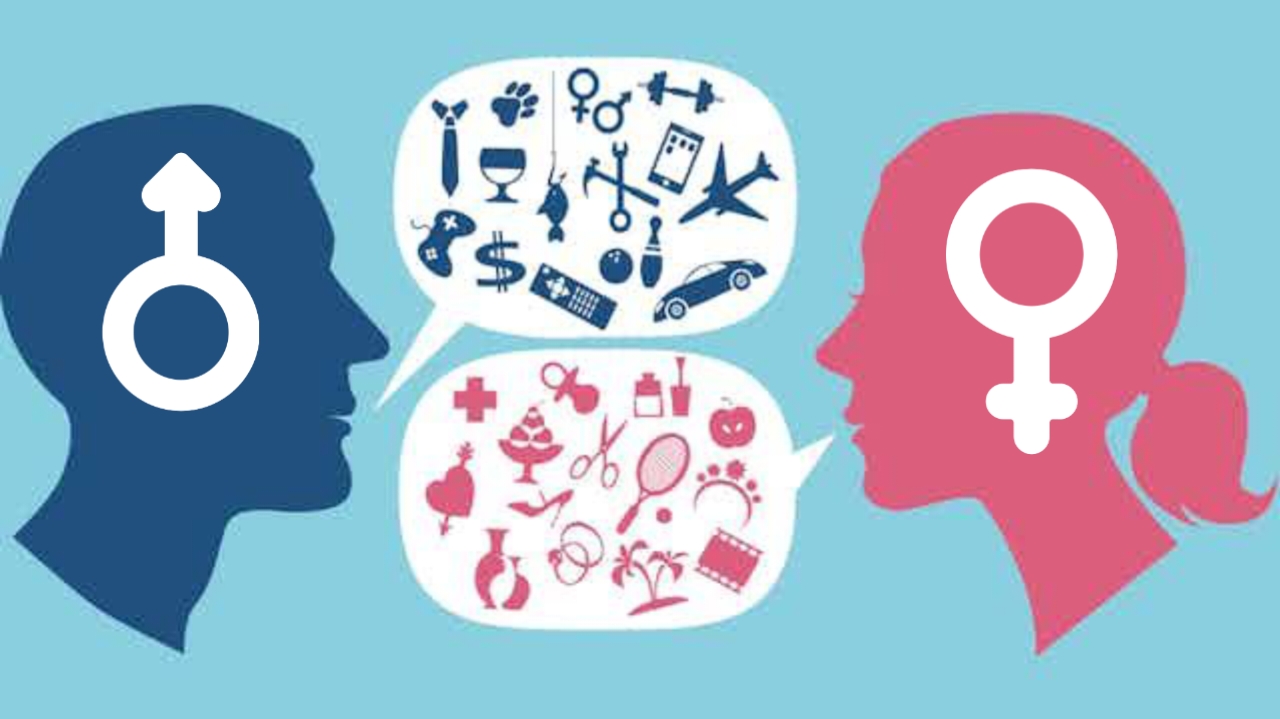
BAHASA adalah cermin dari cara kita memandang dunia. Ia menyimpan nilai, prasangka, sekaligus harapan dalam satu waktu.
Karena itu, bahasa bukan sekadar alat komunikasi. Ia adalah ruang politik, sosial, dan budaya yang diam-diam membentuk cara pikir kita setiap hari.
Menjelang hari kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, kita perlu bertanya ulang: sudahkah kemerdekaan itu mencakup semua suara, termasuk dalam cara kita berbahasa?
Bahasa Kita, Cermin Nilai Kita
Secara tata bahasa, bahasa Indonesia tergolong netral. Ia tidak mengenal bentuk maskulin atau feminin sebagaimana dalam bahasa asing seperti Arab atau Jerman.
Baca Juga
- Kekuatan Kepemimpinan Perempuan: Mengubah Paradigma dan Menciptakan Dampak Positif
- Perempuan dan Anak Sebagai Aset Daerah
Kita hanya punya satu istilah: “dokter”, “guru”, “pemimpin”, “penulis”, “wartawan”—tanpa penanda jenis kelamin.
Namun, dalam praktik sosial-budaya, netralitas itu sering kali dilanggar. Muncul istilah “wartawati”, “polwan”, atau “dokter perempuan”—seolah perempuan harus ditandai, sementara laki-laki dianggap sebagai standar.
Menurut cendekiawan muslim progresif Prof. Ulil Abshar Abdalla, ini keliru. “Wartawan adalah representasi profesi, bukan jenis kelamin,” katanya.
Bahasa Indonesia, lanjut beliau, secara struktur sudah cukup inklusif, dan menambahkan embel-embel justru dapat memperkuat sekat-sekat gender yang ingin kita hapuskan.
Ketika Netralitas Dibelokkan Budaya
Permasalahan utamanya bukan pada bahasa, tapi pada budaya pengguna bahasa.
Dalam budaya patriarkal, istilah netral kerap terasosiasi pada laki-laki. “Pemimpin” otomatis dibayangkan sebagai sosok laki-laki. Maka lahir sebutan seperti “pemimpin perempuan”—seolah perempuan adalah pengecualian.
Inilah yang disebut markedness dalam teori linguistik kritis: laki-laki menjadi bentuk tidak bertanda (default), perempuan harus diberi tanda.
Dalam kerangka teori feminis strukturalis, ini mencerminkan relasi kuasa simbolik dalam bahasa—bahwa bahasa tidak netral, melainkan produk dari sistem sosial yang timpang.
Bahasa Membentuk Realitas Sosial
Dalam perspektif sosiolinguistik, bahasa tidak hanya mencerminkan realitas sosial, tetapi juga membentuknya.
Ketika kita menyebut perempuan sebagai “wartawati”, kita sedang menciptakan batas. Kita membentuk imajinasi kolektif bahwa “wartawan” adalah milik laki-laki, dan perempuan hanya tambahan.
Di sinilah pentingnya bahasa inklusif sebagai strategi perubahan sosial. Sejalan dengan SDG 5: Kesetaraan Gender, penggunaan bahasa yang adil merupakan bagian dari penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di ruang publik, termasuk di media, pendidikan, dan kebijakan.
Tugas Bersama: Mendidik Bahasa yang Setara
Bahasa yang inklusif tidak akan tumbuh tanpa kesadaran kolektif. Dan kesadaran ini harus dimulai dari lembaga-lembaga utama: pendidikan dan media.
Dalam konteks SDG 4: Pendidikan Berkualitas, penting untuk menghadirkan narasi yang mencerminkan keragaman dan kesetaraan dalam buku teks, modul ajar, dan ruang kelas.
Guru perlu membiasakan istilah profesi yang tidak bias. Media perlu berhenti memberi label seperti “ilmuwati cerdas” atau “polwan cantik”—karena frasa semacam itu melekatkan stereotip tidak perlu pada capaian profesional.
Bahasa adalah ruang belajar. Dan siapa yang belajar dari bahasa yang bias, akan tumbuh dalam ketimpangan.
Merdeka yang Inklusif Dimulai dari Bahasa
Menjelang hari kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, sudah saatnya kita memaknai kemerdekaan bukan hanya dalam makna fisik dan politik, tetapi juga makna simbolik dan kultural.
Kemerdekaan hari ini harus dimaknai secara lebih inklusif. Itu artinya: memberi ruang setara dalam bahasa, menyetarakan siapa yang diucap dan bagaimana ia disebut.
Karena kemerdekaan tanpa bahasa yang membebaskan adalah kemerdekaan yang timpang.
Bahasa yang Membebaskan
Mulailah dari hal sederhana: gunakan istilah profesi tanpa penanda gender jika tidak relevan. Sebut “pemimpin”, “penulis”, “jurnalis”, atau “aktivis” tanpa embel-embel yang memisahkan.
Karena setiap kata adalah pintu. Dan kita semua punya kuasa untuk menentukan ke mana pintu itu mengarah: pada ketimpangan yang kita warisi, atau pada keadilan yang ingin kita bangun.
Bahasa yang inklusif adalah bagian dari Indonesia yang merdeka—untuk semua, bukan hanya untuk sebagian.
*Ditulis oleh: Raden Siska Marini.
![]()









